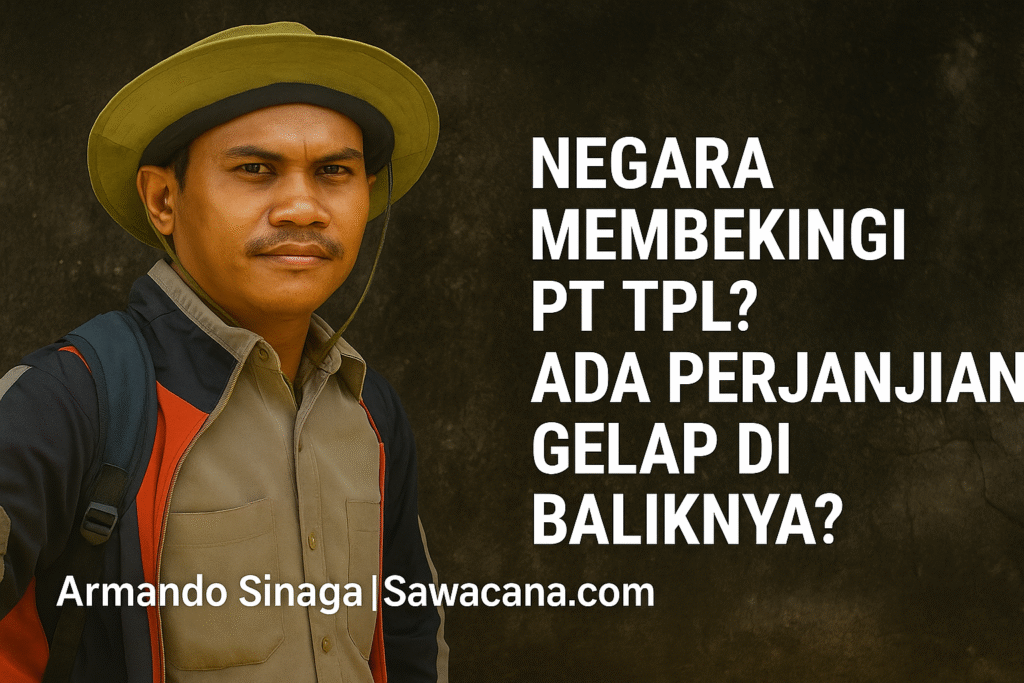Gelombang penolakan terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL) kian meluas di Sumatra Utara. Dari marga-marga adat hingga kelompok pecinta lingkungan, suara yang sama menggema: tolak keberadaan PT TPL. Namun, di tengah desakan masyarakat adat dan sorotan publik, pemerintah tetap bergeming. Izin operasional perusahaan bubur kertas ini tak kunjung dicabut. Sikap ini menimbulkan tanya besar—apakah negara diam-diam membekingi PT TPL, atau ada perjanjian gelap yang membuat pemerintah memilih berpihak pada korporasi ketimbang rakyat?
Pertanyaan itu kian relevan ketika fakta di lapangan menunjukkan dampak lingkungan yang serius: kerusakan hutan, konflik agraria, dan terancamnya ruang hidup masyarakat adat. Penolakan sudah berlangsung puluhan tahun, tetapi kebijakan pemerintah tak pernah menyentuh inti masalah. Keteguhan negara membiarkan PT TPL beroperasi memunculkan dugaan bahwa ada kepentingan tersembunyi yang lebih kuat daripada suara rakyat dan keselamatan ekosistem Danau Toba.
Sebagai penulis, saya menilai pemerintah wajib memutus segala hubungan yang merugikan masyarakat adat. Tidak ada alasan moral dan hukum bagi negara untuk terus menoleransi praktik yang berpotensi merampas tanah leluhur. Menunda pencabutan izin sama saja dengan memperpanjang penderitaan dan membuka peluang kerusakan yang lebih besar. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan perisai bagi kepentingan korporasi.
Jejak Panjang Konflik PT TPL dan Masyarakat Adat
Sejak awal berdirinya pada era 1980-an, PT Toba Pulp Lestari (TPL) telah menjadi sumber sengketa yang tak kunjung reda di kawasan Danau Toba. Konflik bermula dari kebijakan konsesi hutan industri yang dinilai tumpang tindih dengan tanah ulayat masyarakat adat. Penolakan demi penolakan meletup setiap kali perusahaan memperluas areal tanam eukaliptus. Aksi protes, mediasi, hingga gugatan hukum sudah berlangsung puluhan tahun, tetapi akar masalah—pengakuan hak tanah leluhur—belum juga diselesaikan. Di tengah situasi itu, perpanjangan izin PT TPL terus berulang, memperkuat kesan bahwa kepentingan korporasi lebih diutamakan ketimbang keadilan bagi warga adat.
Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga memicu ketegangan sosial yang mendalam. Lahan yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan masyarakat adat—tempat bertani, meramu obat, dan melaksanakan ritual budaya—perlahan berubah menjadi hamparan perkebunan eukaliptus. Warga yang menolak sering menghadapi intimidasi, proses hukum, hingga kriminalisasi. Sementara itu, upaya negosiasi berulang kali menemui jalan buntu karena pemerintah terkesan lebih melindungi kepentingan investasi daripada mendengarkan aspirasi komunitas adat.
Melihat perjalanan panjang konflik ini, wajar bila masyarakat adat dan pegiat lingkungan menuntut pemerintah meninjau ulang seluruh perizinan PT TPL. Tanpa keberanian politik untuk memutus mata rantai ketidakadilan, konflik akan terus berulang dan kepercayaan publik kepada negara semakin tergerus. Desakan ini sekaligus menjadi jembatan menuju pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa pemerintah terlihat melindungi PT TPL meskipun penolakan semakin meluas? Pertanyaan inilah yang akan diulas pada bagian berikutnya.
Mengapa Pemerintah Terlihat Melindungi PT TPL?
Sikap pemerintah yang berulang kali menunda pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) menimbulkan pertanyaan mendalam: apa alasan sebenarnya di balik kebijakan ini. Banyak pihak menduga ada pertimbangan ekonomi dan politik yang membuat pemerintah terkesan menutup mata terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak adat. Mulai dari penerimaan pajak, investasi asing, hingga potensi lobi industri pulp dan kertas, semua disebut-sebut sebagai faktor yang menahan langkah tegas. Di sisi lain, mekanisme pengawasan lingkungan dan penegakan hukum tampak lemah, memberi ruang bagi perusahaan untuk terus beroperasi tanpa sanksi berarti.
Dalam berbagai kasus di sektor sumber daya alam, relasi antara pemerintah dan korporasi kerap diwarnai oleh kontrak jangka panjang, kepentingan pajak, dan tekanan investor. Pola serupa diduga terjadi pada PT TPL. Setiap kali perpanjangan izin mendekat, muncul narasi “kepentingan nasional” atau “penyerapan tenaga kerja” sebagai alasan menunda pencabutan. Namun, data kerusakan hutan dan laporan pelanggaran hak adat menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi yang dijanjikan tidak sebanding dengan biaya ekologis dan sosial yang ditanggung masyarakat. Ketidaktransparanan perjanjian bisnis ini membuat publik sulit menilai sejauh mana negara benar-benar bebas dari pengaruh lobi industri.
Tanpa audit independen dan keterbukaan dokumen perjanjian, dugaan adanya “perjanjian gelap” antara pemerintah dan PT TPL akan terus menghantui. Setiap keterlambatan langkah hukum hanya menambah ketidakpercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi lingkungan dan hak masyarakat adat. Karena itu, desakan agar pemerintah segera membekukan izin PT TPL bukan sekadar tuntutan emosional, melainkan langkah mendesak untuk memulihkan keadilan ekologis.
Seruan Mendesak: Cabut Izin, Pulihkan Tanah Leluhur
Di tengah ketidakpastian hukum dan tudingan adanya perjanjian gelap, pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditunda. Bagi masyarakat adat di sekitar Danau Toba, izin yang terus diperpanjang sama saja dengan menghalalkan perampasan tanah leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Puluhan tahun protes dan mediasi gagal membuahkan hasil, sehingga langkah tegas berupa pembekuan dan pencabutan izin dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk menghentikan kerusakan hutan, memulihkan hak ulayat, dan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara.
Langkah tegas tersebut harus disertai audit independen terhadap seluruh proses perizinan dan kegiatan PT TPL. Pemerintah perlu membuka dokumen kontrak, peta konsesi, hingga laporan dampak lingkungan secara transparan. Tanpa keterbukaan, publik akan terus meragukan komitmen negara dalam melindungi hak masyarakat adat. Selain itu, pemulihan ekosistem harus menjadi prioritas, termasuk rehabilitasi hutan, pemulihan sumber air, dan pengembalian lahan yang telah diambil kepada pemilik ulayat yang sah.
Di sisi lain, pengakuan hukum atas tanah adat perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Mekanisme seperti penetapan hutan adat, peraturan daerah yang melindungi hak ulayat, serta pengawasan ketat terhadap investasi baru menjadi kunci pencegahan. Dengan demikian, pencabutan izin PT TPL tidak hanya menyelesaikan konflik hari ini, tetapi juga memastikan keadilan ekologis dan sosial bagi generasi mendatang.
Disclaimer / Penafian
Tulisan ini sepenuhnya merupakan pendapat pribadi penulis sebagai warga negara yang menggunakan hak kebebasan berekspresi. Semua informasi yang disertakan bersumber dari data dan pemberitaan yang sudah tersedia di ruang publik. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menuduh, memfitnah, atau merugikan pihak mana pun, melainkan sebagai kritik dan ajakan dialog demi kepentingan lingkungan serta hak masyarakat adat. Jika ada pihak yang keberatan, hak jawab atau klarifikasi akan dihormati sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[penulis:armando sinaga]